Memantau Pelaksanaan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual
PARBOABOA - The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) pernah membuat riset ihwal bagaimana pengadilan di negeri kita ini menangani perkara kekerasan seksual, termasuk perkosaan, pada kurun 2018-2020.
Temuannya? Mayoritas, sekitar 70 persen, bukti ilmiah yang digunakan di persidangan adalah hasil pemeriksaan fisik (visum et repertum).
Hasil pemeriksaan psikiatri (visum et repertum psikiatrikum) minim sekali dipakai. Padahal, itu sesungguhnya bisa menjadi bahan pertimbangan penting sebelum majelis hakim membuat putusan berdasarkan keyakinan diri mereka.
Sekian lama, alat bukti yang digunakan di pengadilan kita saat memverifikasi apakah telah terjadi pemerkosaan atau tidak adalah hasil visum et repertum dan keterangan saksi. Dua unsur ini yang paling menentukan keyakinan hakim.
Sementara, bukti fisik—luka di alat kelamin dan sisa sperma, terutama—gampang sekali hilang. Korban sendiri belum tentu akan langsung menjalani visum begitu kejadian usai.
Penggunaan visum et psikiatrikum sebagai alat bukti sebetulnya bukan hal baru. Tapi, pembiaran untuk tidak mencari bukti ini sudah terlalu lama sehingga seolah-olah hal baru.
”Jadi, di Indonesia ini kita sangat lama berhadapan dengan para aparat penegak hukum yang tidak cukup punya komitmen mencari bukti psikiatrikum,” ucap peneliti di ICJR Maidina Rahmawati.
“Kalau polisi, jaksa, dan hakim hanya berpatokan pada visum fisik maka mereka tidak akan dapat merespon perkara dengan tepat.”
Selain komitmen penegak hukum yang kurang untuk menghadirkan bukti psikiatri, ada lagi sejumlah ganjalan yang sangat serius. Tenaga ahli yang bisa melakukan pemeriksaan psikiatri itu sangat sedikit, antara lain.
Psikiater di Indonesia total jenderal sekitar 1.200 saja. Padahal, negeri kita ini berpenduduk hampir 280 juta jiwa. Di Jakarta sendiri, seperti kata Maidina Rahmawati, cuma Rumah Sakit Tarakan yang punya ahli psikiatri yang bisa menangani kasus kekerasan seksual. Kalau di DKI saja demikian bisa kita bayangkan seperti apa keadaan di daerah.
Keyakinan hakim sering pun terkadang menjadi masalah juga.
“Seperti dalam kasus pelecehan seksual yang dilakukan dosen Universitas Riau. Bukti visum psikiatrikum sudah dihadirkan. Korban juga sudah bersaksi dan ada pemeriksaan psikologis yang menunjukkan bahwa korban trauma. Tapi masalahnya balik lagi: kita sangat bergantung pada keyakinan hakim,” peneliti ICJR itu mencontohkan.
Seorang mahasiswa jurusan Hubungan Internasional Universitas Riau (UNRI) mengupload video di Instagram-nya pada 4 November 2021. Intinya, ia telah dilecehkan Dekan Fisipol UNRI yang merupakan pembimbing skripsinya, Syafri Harto. Pipi kiri dan keningnya dicium. Ia kabur saat bibirnya hendak disasar.
Esoknya, korban melapor ke Polresta Pekanbaru. Hari itu juga seratusan mahasiswa berunjuk rasa di Rektorat UNRI.
Syafri Harto menyatakan tuduhan itu fitnah yang dibuat setelah terbetik kabar bahwa dirinya akan maju tahun depan sebagai calon rektor. Ia menyatakan akan menuntut mahasiswa bimbingannya itu Rp 10 miliar.
Perkara berlanjut ke pengadilan. Tuntutan jaksa 3 tahun hukuman penjara. Tapi, majelis hakim PN Pekanbaru menyatakan unsur dakwaan tidak terpenuhi. Syafri Harto pun divonis bebas.
“Keyakinan hakim itu memang sentral. Masalahnya, kita tidak punya aturan yang baku untuk dapat memahami sampai level mana kita bisa menerima bahwa keyakinan hakim itu bisa dibenarkan sebagai keputusan. Itu juga menjadi catatan kami,” lanjut Maidina Rahmawati.
Terburu-buru
Seorang anak telah menjadi korban perkosaan di sebuah tempat di Nusa Tenggara Timur. Korban kemudian menuntut balas. Pelaku, seorang penatua gereja, pun dihabisinya. Akibatnya, anak itu diganjar keras oleh majelis hakim.
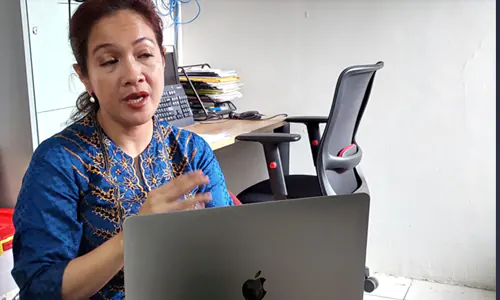
Kasus ini mendapat perhatian khusus dari Natali Widiasih, Kepala Divisi Psikiatri Forensik di Departemen/KSM Ilmu Kesehatan Jiwa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK-UI) – Rumah Sakit Umum Pusat Nasional dr. Cipto Mangunkusumo (RSUPN—RSCM).
“Sebenarnya ada hal yang mesti diperhatikan sebelum menjatuhkan hukuman. Kita harus lihat inner mens rea-nya [keadaan mental] untuk pembuktian. Kita harus lihat apa yang ada dalam pikiran pelaku sekaligus korban. Saat pengadilan pertama, bisa jadi hal ini tidak terungkap karena harus buru-buru diputuskan. Padahal kasusnya kan kompleks,” kata Ketua Program Studi (Prodi) Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa FK-UI itu.
Kasus perkosaan dan pembunuhan yang pelakunya adalah anak di bawah umur 10 tahun itu, menurut dia, kompleks. Karena faktanya anak itu di bawah umur, memiliki IQ terbatas, dan kosa katanya minim sehingga sulit menjelaskan seluruh cerita.
Masalahnya, otoritas yang menangani di kepolisian banyak yang maunya serba cepat. Hanya melihat adegan yang diperagakan saja; tidak membuat assessment (penilaian) mendalam berdimensi psikologi dan psikiatri.
Padahal, pembuktian kejiwaan untuk kepentingan hukum sudah ada aturannya yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum. Harusnya prosedurnya merujuk ke situ.
“Di kita kan nggak mau pakai itu. Maunya cepat-cepat. Di kita ini juga lucu. Belum terbukti (salah atau benar) udah langsung diposting di media oleh otoritas. Ini justru membuat orang jadi takut menjalani proses hukum,” tutur Natali Widiasih.
Kalau psikiater, tutur dia, lain. Bekerja mesti cermat, tak boleh tergesa.
“Kenapa cara kerja kami lama ya karena tugas kami itu tanggung jawabnya dunia-akhirat. Nanti saya akan ditanya Tuhan. Ha, ha, ha… Kita bertanggung jawab well-being orang. Jangan sampai nanti kalau datanya kurang, orang ini akan ditanya-tanya lagi. Kasihan kan. Dia mengalami secondary raped perkosaan kedua]. Itu membahayakan diri mereka.”
Tugas psikiater yang menangani kasus tindak kekerasan seksual adalah mengatasi gangguan kejiwaan pada diri korban. Satu lagi, membuat penilaian untuk kepentingan peradilan. Tugas ini tak bisa dilakukan sendiri melainkan bersama tim.
“Di Indonesia, tidak banyak psikiater yang berani ngerjain yang kayak gini. Apalagi skill kita untuk kasus tertentu tidak seragam. Nggak banyak yang mau mengerjakan forensik ini karena lebih banyak tekanan, lebih banyak risiko, dan bayarannya nggak ada. Jumlah konsultan yang seperti saya ini, kurang dari 10,” tutur Natali Widiasih, doktor yang banyak menangani kasus kekerasan seksual.
PERMA
Riset indeksasi keputusan yang dilakukan The Institute for Criminal Justice Reform itu tak hanya melihat bagaimana hakim mengadili perkara kekerasan seksual.
Mereka juga mencermati mulai dari putusan-putusannya, ancaman pidananya, vonisnya, pertimbangan hakimnya, hingga catatan ganti ruginya (restitusi).
“Jadi, segala aspek perlu dilihat. Tidak hanya korban (perempuan), tetapi juga pelaku dan saksi. Hakim harus melihat itu. Bahasan tentang relasi kuasa pun mulai dimasukkan.
Artinya kekerasan seksual terjadi bukan karena nafsu semata, tetapi ada juga relasi kuasa,” jelas peneliti di ICJR, Maidina Rahmawati.
Hasil riset itu mereka jadikan kemudian dasar untuk mengadvokasi para penegak hukum. Tak hanya sebatas meriset, mereka ikut juga mendorong terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) 3/2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
Di PERMA itu terdapat pelbagai arahan termasuk yang terkait stereotype gender, relasi kuasa, dan kerentanan gender. Berikut ini gambarannya.
Pasal 4
Dalam pemeriksaaņ perkara, hakim agar mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan: a. ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara; ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak b. pada akses keadilan; c. diskriminasi; d. dampak psikis yang dialami korban; ketidakberdayaan fisik dan psikis korban; e. Relasi Kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak f. berdaya; dan g. riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/ saksi.
Pasal 5
Dalam pemeriksaan Perempuan Berhadapan dengan Hukum hakim tidak boleh: a. menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi Perempuan Berhadapan dengan Hukum; b membenarkan terjadinya Diskriminasi Terhadap Perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias Gender; mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku; dan mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang d. mengandung Stereotip Gender.
Pasal 7
Selama jalannya pemeriksaan persidangan, hakim agar mencegah dan/atau menegur para pihak, penasihat hukum, penuntut umum dan/atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
Secara konseptual, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 3/2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum ini merupakan sebuah lompatan besar. Lagi-lagi, masalahnya adalah penerapan. Hakim dan jaksa sendiri umumnya masih saja berlanggam lama sehingga enggan menjalankannya.
Pada 2022 muncul regulasi yang jauh lebih progresif. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), namanya. Fajar harapan yang didambakan para pencari keadilan pun merekah.
UU TPKS
Penuntut umum, dan hakim yang menangani perkara tindak kekerasan seksual (TPKS) harus memiliki integritas dan kompetensi dalam menangani perkara berperspektif HAM dan korban. Mereka juga telah mengikuti pelatihan terkait penanganan perkara TPKS. Demikian menurut UU ini.
Alat buktinya tidak lagi hanya visum et reppertum dan kesaksian. Pasal 24 berbunyi:
(2) Termasuk alat bukti keterangan Saksi yaitu hasil pemeriksaan terhadap Saksi dan/atau Korban pada tahap penyidikan melalui perekaman elektronik. (3) Termasuk alat bukti surat yaitu: a. surat keterangan psikolog klinis dan/atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa; b. rekam medis; c. hasil pemeriksaan forensik; dan /atau d. hasil pemeriksaan rekening bank.
Sedangkan ihwal saksi, Pasal 25 berkata:
(1) Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan I (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.
(2) Keluarga dari terdakwa dapat memberi keterangan sebagai Saksi di bawah sumpah/janji, tanpa persetujuan terdakwa.
Pidana penjara dan pidana dendanya juga serius. Pula, ada aturan tentang ganti rugi (restitusi) untuk korban.
Perkara tindak pidana kekerasan seksual, menurut UU TPKS, tidak dapat diselesaikan di luar proses peradilan kecuali terhadap pelaku anak sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Jadi, sekali lagi, regulasi ini sungguh sebuah terobosan besar terlebih kalau dilihat dari jurusan para korban. Begitupun, kelemahannya ada pula yang fatal yaitu pensubordinasian aturan tentang perkosaan. Hal yang mengakibatkan kasus tidak ditangani dengan UU TPKS melainkan dengan KUHP.
Ihwal pemasukan aturan tentang pemerkosaan ke ayat 2 Pasal 4 UU TPKS, penjelasannya diberikan peneliti The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Maidina Rahmawati.
“Saat kita sedang mendorong revisi UU KUHP, UU TPKS pun sedang dipersiapkan. Jadi, peristiwanya paralel. Itu sebabnya antara lain perkosaan tidak berhasil masuk di UU TPKS. Waktu itu yang memimpin perancangan KUHP dan UU TPKS adalah Prof Eddy, Wakil Menteri Hukum dan HAM [Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy Hiariej],” ungkap dia.
Yang disahkan lebih dulu adalah UU TPKS. “Saat itu Prof. Eddy bilang perkosaan itu masuknya di KUHP, tidak di TPKS. Jadi, yang berhasil kita dorong hanyalah memasukkan itu di UU TPKS pasal 4 ayat 2.
Implikasinya, memang secara aturan hukum pidana, dakwaan akan merujuk ke pasal 285 KUHP.” [Bunyinya: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”]
Seperti halnya PERMA 3/2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, UU TPKS pun tak mulus dalam penerapan. Meski telah 2 tahun berlaku, ia masih kurang dihiraukan oleh para penyidik, jaksa, dan hakim.
SDM Payah
Seorang remaja perempuan berusia 15 tahun diperkosa di oleh sekitar 11 orang di Sulawesi Tengah. Satu dari pelaku adalah Brimob. Kapolda kemudian memberi keterangan pers.
“Kapolda menyebutkan bahwa itu bukan perkosaan massal tapi satu per satu. Korban tidak diperkosa rame-rame. Yang terjadi adalah persetubuhan,” kata Alissa Wahid.
Psikolog, pendidik, pegiat Jaringan Gusdurian, dan juga anak sulung mantan presiden Abdurrahman Wahid ini menilai Kapolda itu tidak memiliki perspektif UU TPKS.
“Kok bisa dia menyebut ini persetubuhan atau wish consent [mau sama mau]? Di undang-undang TPKS jelas bahwa kalau kelompok rentan itu, termasuk anak-anak, sekalipun terkesan menerima tapi sebetulnya di bawah relasi kuasa. Karena itu tidak boleh disebut sebagai persetubuhan biasa; kecuali jika pelaku dan korban sesama anak-anak.”

Sebagus apa pun aturan, itu akan sia-sia saja kalau tak bisa dijalankan. UU TPKS yang disahkan DPR pada 12 April 2022 tak terkecuali. Setelah 2 tahun lebih berlaku, regulasi ini belum kunjung bernas.
Masih banyak pekerjaan rumah yang mesti dibereskan. Yang paling mendasar adalah membuat turunan-turunannya yang lebih konkrit dan mudah diterapkan. Lantas, meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang akan menjalankannya.
Bukan hanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK); tapi juga penyidik, penuntut umum, dan hakim yang harus dilatih khusus. Itu tentu saja memerlukan waktu dan biaya raksasa.
Dalam pembangunan SDM ini, apa yang terjadi dalam sistem peradilan pidana anak bisa dijadikan contoh.
“Penyidik, penuntut umum, dan hakimnya harus memiliki sertifikat untuk menangani perkara anak. Penyiapannya memerlukan tempo yang cukup lama.
Maka, tenggat waktu pemberlakuan UU SPPA [Sistem Peradilan Pidana Anak] ini pun lama,” ucap Albertina Ho, ketua majelis hakim yang menyidangkan kasus suap pegawai pajak Gayus Tambunan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan perkara yang melibatkan mantan ketua KPK Antasari Azhar.
Sementara UU TPKS langsung diberlakukan tahun 2022 itu juga. Mestinya perlu waktu yang cukup lama untuk menyiapkan bukan hanya manusianya tapi juga sarana dan prasarana yang lain.
Memang, dalam UU TPKS dinyatakan bahwa untuk sementara apabila SDM yang sesuai kualifikasi belum ada maka bisa saja Kapolri, Jaksa Agung, dan Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan SK dan memberikan kewenangan kepada penyidik, penuntut umum, maupun hakim yang disebutkan dalam SK itu untuk menangani perkara-perkara tindak pidana kekerasan seksual.
“Tetapi kembali lagi: kalau kita melihat idealnya, mereka yang ditunjuk itu harus mengikuti pelatihan juga agar lebih matang dan memahami. Soalnya, banyak sekali lex specialis yang diatur khusus dalam undang-undang TPKS,” lanjut anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK tersebut.
Alissa Wahid yang dalam 5 tahun terakhir bekerja sama dengan pemerintah mengatakan, masih banyak kendala dalam meningkatkan mutu SDM yang akan menangani perkara kekerasan seksual. Salah satunya adalah mendidik begitu banyak orang.
“Katakanlah jumlah Polsek sama dengan kecamatan. Berarti kita harus mendidik puluhan ribu personil polisi. Belum lagi harus melatih psikolog dan psikiater,” ucap dia.
Membangun SDM yang mumpuni selalu menjadi pekerjaan terberat. Sementara, tanpa itu regulasi sehebat apa pun tak akan banyak faedahnya. Semoga saja UU TPKS yang hebat itu akan digdaya.
Reporter: Rin Hindryati dan P. Hasudungan Sirait






